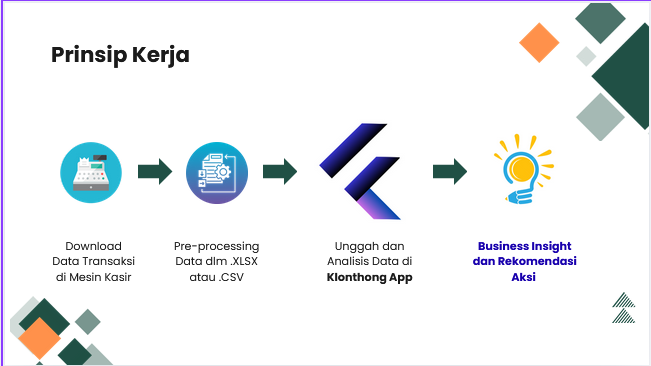Dinamika organisasi paguyuban pemerintahan desa belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Sorotan muncul bukan karena kontribusi nyata mereka bagi kemajuan desa, melainkan karena fenomena kepemimpinan yang menyimpang dari ruh organisasi.
Kini muncul orang-orang memimpin asosiasi desa tanpa pernah menjabat sebagai Kepala Desa, perangkat desa, atau bahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Parahnya, ada pengurus yang bahkan tidak berdomisili di desa, namun mengambil posisi kunci memimpin organisasi yang seharusnya lahir dari, oleh, dan untuk ekosistem desa.
Para pemimpin non-struktural ini sering berkelit dengan dalih bahwa kepedulian tulus mendorong mereka mengambil alih kepemimpinan. Namun, kita mendapati fakta bahwa sebagian besar justru sibuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) demi kepentingan pribadi.
Mereka merancang mekanisme Musyawarah Nasional (Munas) secara eksklusif dan menjadikan organisasi desa sebagai kendaraan politik yang melenceng jauh dari tujuan awal sebagai wadah perjuangan aparatur desa.
Paguyuban desa, pada hakikatnya, merupakan organisasi profesi yang menuntut etika dan kompetensi jelas dari para pengurusnya. Kita dapat melihat analogi pada paguyuban kepala daerah atau paguyuban anggota DPRD, di mana syarat menjadi pengurus mengharuskan seseorang sedang atau pernah menjabat di posisi tersebut. Logika ini sangat beralasan, sebab mustahil seseorang memimpin organisasi profesi tanpa pernah menjalani bidang kompetensi yang relevan.
Prinsip yang sama mutlak berlaku untuk organisasi pemerintahan desa. Seseorang secara moral dan etik tidak memiliki legitimasi memimpin paguyuban desa jika dia tidak pernah menjadi Kepala Desa, perangkat desa, atau anggota BPD. Pengalaman struktural tidak bisa digantikan hanya dengan klaim kepedulian yang datang dari luar lingkup desa.
Organisasi pemerintahan desa bukanlah sekadar komunitas hobi, melainkan sebuah asosiasi profesional yang mengurus hajat publik, jalur anggaran strategis, dan advokasi regulasi krusial.
Integritas pengurus menjadi syarat primer mengingat organisasi ini bersentuhan langsung dengan kepentingan ribuan aparat desa dan jutaan warga. Tindakan paling menyesatkan terjadi ketika AD/ART sengaja dirancang bukan untuk memperkuat lembaga, melainkan hanya untuk mengukuhkan posisi elite kecil yang berkuasa. Mekanisme Munas sering kali ditempatkan di lokasi yang jauh dan eksklusif, seperti di ibu kota, tanpa mempertimbangkan aksesibilitas mayoritas aparat desa yang memiliki keterbatasan anggaran dan waktu.
Jika paguyuban desa hanya dapat diakses oleh segelintir orang, organisasi tersebut otomatis kehilangan marwah dan representasi sejatinya. Apalagi jika para pengurus yang terpilih kemudian diketahui tidak memiliki rekam jejak dalam jabatan pemerintahan desa. Ini bukan lagi sekadar persoalan etika, tetapi telah merambah pada masalah legitimasi fundamental yang harus segera diperbaiki.
Para penyelenggara desa harus memetik pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Sudah terlalu banyak organisasi yang terpecah belah, bukan karena adanya perbedaan ideologi, tetapi karena kepentingan politik tertentu berhasil memanfaatkan paguyuban desa sebagai wadah mobilisasi massal. Paguyuban desa adalah benteng perjuangan desa, dan harus terbebas dari kepentingan faksi atau kelompok politik di luar sana.
Jika seseorang nekat memimpin organisasi desa tanpa rekam jejak memadai, tanpa pengalaman mengelola pemerintahan desa, dan tanpa pemahaman mendalam tentang beban regulasi di lapangan, maka pertanyaan sederhananya adalah: apa tujuan ia memimpin organisasi ini? Kepedulian murni tidak menuntut kursi ketua, tetapi dapat diwujudkan melalui pendampingan, riset, edukasi, atau advokasi yang suportif. Ketika seseorang yang tidak tinggal, tidak bertugas, dan bukan bagian dari desa bersikeras memimpin, maka publik berhak bertanya tegas: apakah ini dorongan kepedulian, atau sekadar kepentingan terselubung?
Organisasi desa wajib segera kembali kepada fungsi utamanya, yakni memperjuangkan kepentingan desa secara kolektif dan tulus. Tugas mereka adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat tata kelola yang baik, dan menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat maupun daerah. Untuk memastikan fungsi ini berjalan, organisasi membutuhkan pengurus yang memiliki tiga pilar legitimasi penting.
Pertama, diperlukan legitimasi moral yang berarti pengurus tersebut harus pernah mengemban jabatan desa atau setidaknya hidup dan berjuang di dalam ekosistem desa. Kedua, mereka harus memiliki legitimasi struktural yang membuktikan pemahaman mendalam tentang regulasi, mekanisme fiskal desa, serta dinamika sosial desa yang kompleks. Terakhir, pengurus harus memiliki legitimasi kultural, yakni mengakar kuat di desa, bukan hanya mengklaim kepedulian dari jarak yang terlalu jauh.
Paguyuban desa tidak boleh dan tidak akan pernah menjadi panggung politik ambisius atau kendaraan pribadi bagi segelintir orang. Organisasi ini tidak boleh dipimpin oleh individu yang hanya menjadikan desa sebagai slogan tanpa pernah merasakan kerasnya medan pertarungan sesungguhnya.
Kesimpulannya, organisasi desa merupakan pondasi utama perjuangan pemerintahan desa yang keberadaannya harus dijaga dengan integritas, bukan didasari oleh ambisi semata. Oleh karena itu, semua penyelenggara pemerintahan desa harus memastikan bahwa paguyuban desa dipimpin oleh individu-individu yang memiliki rekam jejak, kredibilitas, dan komitmen yang tidak diragukan lagi terhadap kemajuan desa. Mereka harus memimpin, bukan mereka yang tidak pernah menjadi bagian dari desa, tetapi ingin mengatur desa dari luar lingkaran.