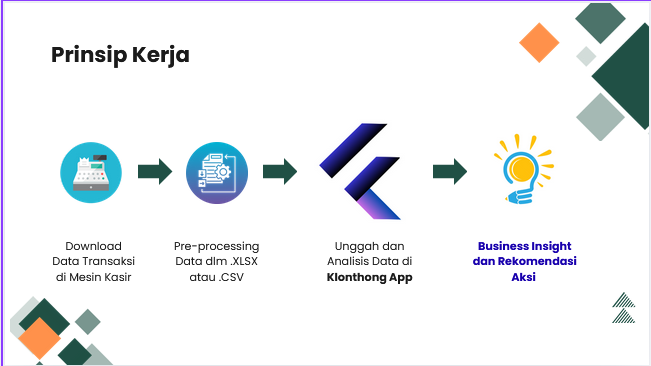Pembangunan nasional kini menempatkan desa sebagai ujung tombak kesejahteraan. Secara filosofis, negara menuangkan otonomi dan kemandirian desa dalam undang-undang. Namun, kami di lapangan justru mengalami dilema. Meskipun secara normatif “kuat”, realitas di desa menunjukkan kelemahan yang jelas. Masih banyak kendala struktural, birokrasi, dan kapasitas yang menghambat pemanfaatan dana secara optimal. Tulisan ini mengangkat fenomena tersebut—mengapa konsep “desa kuat” seringkali tidak terwujud sempurna—dan menawarkan refleksi dari praktik pemerintahan desa.
Secara filosofis dan regulatif, posisi desa sangat strategis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kami kerangka kewenangan, akses sumber daya, dan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan masyarakat. Idealnya, desa menjadi ruang mitigasi kesenjangan pembangunan, memperpendek rantai birokrasi, dan mengedepankan partisipasi. Filosofi ini menuntut desa untuk kuat dalam tata kelola, kuat dalam partisipasi, dan kuat dalam menggerakkan potensi lokal.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan banyak hambatan yang menghambat penguatan filosofis itu. Kewenangan desa seringkali masih terbatas karena pihak atas masih mengendalikan banyak fungsi operasional. Kapasitas aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum selalu memadai untuk mengelola keuangan dan perencanaan secara autentik. Partisipasi masyarakat juga sering bersifat simbolik, tanpa keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi, tuntutan birokrasi dan regulasi yang rumit membuat proses di desa berjalan lambat.
Dari dua sisi tersebut, muncullah sebuah paradoks. Desa dikuatkan secara kebijakan dan filosofis melalui pengakuan, kewenangan, dan dana. Namun, desa justru dilemahkan secara praktis oleh keterbatasan kapasitas dan hambatan implementasi. Kami di desa dianggap sebagai agen pembangunan mandiri, tetapi seringkali tetap bergantung pada arahan yang bersifat top-down. Paradoks ini bukan sekadar teori. Ini adalah realitas yang saya saksikan dalam praktik pemerintahan desa di Cibiru Wetan dan melalui dialog dengan masyarakat.
Para pakar memperkuat analisis ini. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, misalnya, menyoroti pengelolaan dana desa yang masih sangat sentralistik sehingga membuat desa sulit mandiri. Ini sejalan dengan pandangan Dr. Hanif Nurkholis yang mengingatkan agar kita menyinkronkan fakta sejarah desa dengan teori. Jika desa hanya diperlakukan sebagai unit pembangunan teknokratis dan mengabaikan kultur lokal, penguatan filosofis tadi pasti akan terhambat dalam implementasinya.
Pakar lain juga menekankan pentingnya konteks lokal. Sosiolog Dr. Endang Turmudi menyoroti bagaimana relasi kekuasaan lokal dan budaya partisipasi sangat menentukan hasil pembangunan. Rian Nugroho dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia bahkan menegaskan agar kebijakan tidak menjadikan desa sebagai “korban” eksperimen. Pesannya jelas: implementasi program harus relevan dengan kebutuhan nyata desa, bukan sekadar menduplikasi model dari kota atau pusat.
Berdasarkan refleksi ini, saya mengajukan beberapa rekomendasi praktis. Pertama, kita harus fokus pada penguatan kapasitas aparatur desa dan BPD secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah pusat dan daerah harus memberi ruang adaptasi regulasi agar desa fleksibel berinovasi sesuai karakteristik lokal. Ketiga, kita wajib mendorong partisipasi warga yang autentik, di mana masyarakat terlibat sejak perencanaan, bukan hanya sebagai penerima program. Terakhir, pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel.
Paradoks ini adalah tantangan nyata. Sebagai Kepala Desa Cibiru Wetan, saya menyaksikan semangat besar telah dicanangkan, namun medium dan metode implementasi masih belum ideal. Penguatan desa hanya akan bermakna jika kita berhasil menggabungkan kerangka regulatif, kapasitas institusi, partisipasi masyarakat, dan adaptasi lokal. Mari kita tidak hanya berbicara tentang desa yang kuat, tetapi mewujudkannya dalam setiap langkah nyata di lapangan. Desa bukan objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki potensi, tanggung jawab, dan masa depan.