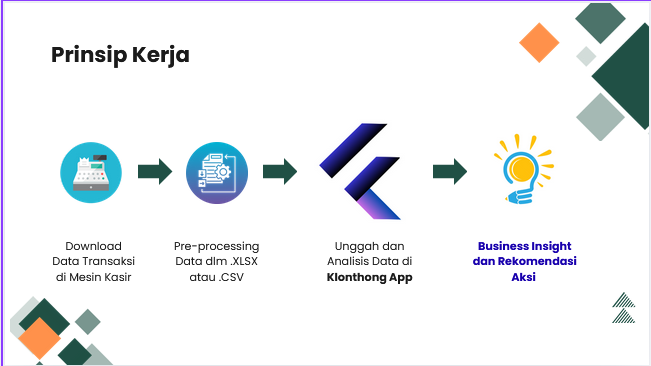Sebuah daerah yang dilabeli “tertinggal” seringkali diidentikkan dengan potret buram: tata layanan pemerintahan yang lamban, infrastruktur yang rapuh, indeks pembangunan manusia (IPM) yang stagnan, serta denyut produktivitas ekonomi yang nyaris tak terdengar. Gambaran ini, meski faktual, bukanlah sebuah kutukan atau vonis permanen. Justru sebaliknya, pelabelan “daerah tertinggal” harus dimaknai sebagai sebuah argumentasi kebijakan: ini adalah metode pemilahan esensial agar intervensi dan kebijakan afirmasi dari pemerintah dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Penetapan ini bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala. Jika sebelumnya kita merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, kini landasan hukumnya telah diperbarui. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 menjadi rujukan terbaru. Data ini menunjukkan kabar baik: jumlah daerah tertinggal menurun signifikan dari 122 menjadi 62 kabupaten.
Angka ini bukan sekadar statistik. Penurunan ini adalah bukti bahwa “pengentasan” adalah hal yang mungkin. Namun, ini juga melahirkan konsekuensi logis: 62 daerah yang tersisa membutuhkan pendekatan yang jauh lebih khusus dan spesifik, karena mereka adalah daerah-daerah dengan tantangan paling kompleks.
Konsekuensinya, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan “sapu jagat”. Program penanganan mereka membutuhkan “percepatan pembangunan”. Tujuannya adalah untuk menekan tingkat kesenjangan (gap) yang menganga. Argumentasinya jelas: bila kesenjangan ini dapat ditekan, maka angka kerentanan sosial antar-daerah—kecemburuan, ketimpangan akses, dan potensi konflik—secara otomatis akan menurun.
Di sinilah letak inti permasalahannya. Percepatan tidak akan pernah lahir dari repetisi atau cara-cara lama. Untuk itu, setiap kegiatan pembangunan di daerah tertinggal harus didesain untuk mampu melahirkan dan menumbuhkan tradisi kreatif dan inovatif.
Inovasi, bagaimanapun, bukanlah sesuatu yang bisa diimpor secara utuh. Ia hanya akan tumbuh subur bila ada ekosistem yang mendukungnya. Ekosistem ini adalah siklus transformasi pengetahuan dan pertukaran praktik baik (best practices). Agar siklus ini berjalan, ada satu prasyarat mutlak: kemampuan untuk mengodifikasi. Daerah harus mampu memetakan, merumuskan, dan mendokumentasikan praktik-praktik baik mereka secara terstruktur agar mudah disebarluaskan.
Argumentasi ini bukan sekadar teori. Tengoklah Kabupaten Bondowoso di Jawa Timur. Daerah ini adalah salah satu daerah dari 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal untuk periode 2014-2019.. Namun, alih-alih pasrah pada label, mereka memilih bertarung dengan cara yang inovatif: menjawab masalah inti “rendahnya produktivitas ekonomi” dan “rendahnya nilai tukar petani”.
Inovasi itu terwujud dalam branding “Bondowoso Republik Kopi” (BRK). Ini bukan sekadar slogan, tetapi sebuah model bisnis dan intervensi sosial yang terstruktur. Sadar memiliki potensi kopi arabika Ijen-Raung yang unik, Pemkab Bondowoso tidak sekadar memberi bantuan pupuk. Mereka bertindak sebagai fasilitator, mengonsolidasikan petani ke dalam klaster-klaster, memberikan pendampingan intensif tentang proses pascapanen, dan yang terpenting: membangun brand bersama.
Apa yang dilakukan Bondowoso adalah contoh sempurna dari inovasi partisipatif. Mereka beralih dari logika menjual komoditas (biji kopi mentah murah) ke logika menjual nilai (kopi specialty dengan branding kuat). Inovasi ini secara langsung meningkatkan kapasitas SDM (petani), membuka lapangan kerja baru (roaster, barista, packaging), dan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Mereka mengodifikasi praktik baik mereka—dari budidaya hingga branding—sehingga bisa direplikasi oleh kelompok tani lain. BRK adalah upaya in-progress untuk mendongkrak IPM dan PDRB dari dalam.
Contoh Bondowoso memperkuat argumen bahwa sebuah pembangunan hanya dapat dianggap inovatif bila keseluruhan prosesnya—dari perencanaan hingga pengawasan—mampu merangsang kreativitas dan partisipasi masyarakat. Inovasi yang top-down seringkali gagal karena tidak memiliki akar sosial. Karena itu, setiap program percepatan pembangunan di daerah tertinggal mutlak harus menyertakan kerja-kerja pendampingan intensif.
Pendampingan bukanlah sekadar “penyuluhan”. Ia adalah proses transfer ilmu, keterampilan, dan kepercayaan diri. Asumsinya sangat kuat: bila pengetahuan dan keterampilan masyarakat meningkat, maka angka dan kualitas partisipasi mereka dalam proses pembangunan akan semakin meningkat pula.
Ketika partisipasi publik berkualitas ini bertemu dengan kepemimpinan yang inovatif, lahirlah kolaborasi multipihak. Pemerintah, masyarakat (dalam hal ini petani kopi), dan sektor privat (eksportir, kafe) dapat duduk bersama sebagai mitra. Kolaborasi inilah yang melahirkan model pembangunan paling ideal: efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, Inovasi Daerah Tertinggal adalah sebuah paradigma kerja baru. Nama Kabupaten Bondowoso sudah tidak maasuk dalam Daftar 62 kabupaten dalam Perpres 63/2020. Prestasi Bondowoso tidak sekadar mencoret nama dari daftar, tetapi membuktikan bahwa ketertinggalan adalah fase yang bisa dilewati, bukan takdir yang harus diterima.