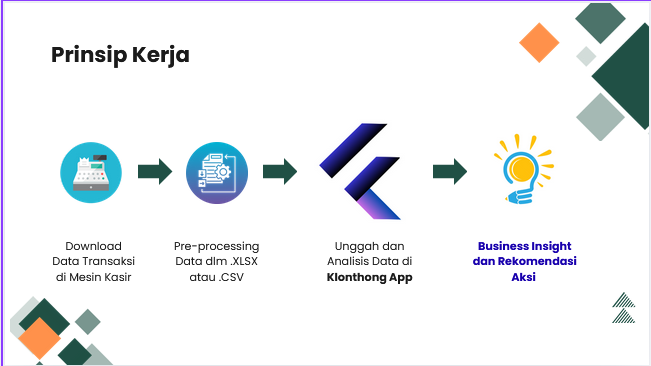Semangat yang melandasi lahirnya Undang-Undang Desa, sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 hingga perubahannya pada UU Nomor 3 Tahun 2025, masih berfokus pada satu titik krusial: kepemimpinan desa. Kepemimpinan memiliki hubungan erat dalam mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, demokratis, dan berkelanjutan. Peran ini adalah mandat strategis yang diemban oleh kepala desa dan perangkatnya untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
Lahirnya UU Desa adalah landasan hukum yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur wilayahnya secara mandiri. Semangatnya jelas: menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pasif. Hal ini menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas mutlak.
Namun, semangat undang-undang tersebut tidak dapat berjalan di ruang hampa. Di sinilah letak argumen utamanya: kepemimpinan desa yang efektif hanya akan terwujud jika mampu mengintegrasikan tata kelola pemerintahan modern dengan nilai-nilai luhur budaya yang hidup di masyarakat. Desa bukanlah sekadar hierarki pemerintahan; ia adalah entitas sosial asli bangsa yang unik.
Kepemimpinan desa yang ideal harus visioner, partisipatif, transparan, dan inovatif. Akan tetapi, karakteristik ini akan rapuh tanpa fondasi budaya. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, toleransi, dan kepedulian sosial adalah “perangkat lunak” yang membuat kepemimpinan itu berfungsi. Pemimpin yang mengabaikan nilai-nilai ini akan kesulitan membangun kepercayaan dan solidaritas.
Sintesis antara tata kelola modern dan kearifan budaya ini bukanlah sekadar teori. Kita dapat menyaksikannya dalam praksis kepemimpinan di Desa Cibiruwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Secara deskriptif, prestasi Desa Cibiruwetan sangat terukur. Pada tahun 2022, desa ini ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai satu dari 10 percontohan desa antikorupsi. Pada tahun yang sama, Cibiruwetan meraih penghargaan nasional untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori pemerintah desa.
Namun, yang lebih penting dari sekadar prestasi adalah cara pencapaiannya. Pencapaian Cibiruwetan didorong oleh inovasi digital seperti aplikasi “Simpel Desa” dan “Balai Desa” untuk kritik dan pengaduan. Ini adalah wujud transparansi modern. Akan tetapi, teknologi ini ditopang oleh fondasi sosial yang kuat, yaitu “Sakola Desa”. Forum ini bukan sekadar tempat belajar formal, melainkan sebuah arena untuk membangkitkan kesadaran kolektif. “Sakola Desa” adalah wujud modern dari musyawarah, tempat aspirasi didiskusikan secara terbuka, dan program dirancang bersama.
Di sinilah Cibiruwetan membuktikan argumennya: mereka menggabungkan akuntabilitas (diawasi KPK dan KIP) dengan partisipasi otentik (melalui Sakola Desa).
Konteks budaya Jawa Barat, tempat desa ini berada, turut memperkuat argumen tersebut. Dedi Mulyadi, saat menjabat Gubernur Jawa Barat, menginisiasi Lomba Kinerja Desa dalam bingkai “Anugerah Sri Baduga”. Penamaan ini bukanlah tanpa alasan. Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi, adalah ikon kepemimpinan legendaris Sunda yang bijaksana. Anugerah ini secara sadar mencari pemimpin desa yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga mengakar pada budaya.
Di tengah meredupnya keteladanan kepemimpinan nasional, ajang seperti Anugerah Sri Baduga menjadi wahana inspiratif untuk menemukan kembali pemimpin yang hadir bersama masyarakat.
Desa Cibiruwetan telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang mengawinkan tuntutan transparansi UU Desa dengan nilai luhur musyawarah budaya adalah kunci keberhasilan. Insyaallah, Desa Cibiruwetan menjadi inspirasi bagi lahirnya kembali “Sri Baduga-Sri Baduga” baru di tengah masyarakat desa.